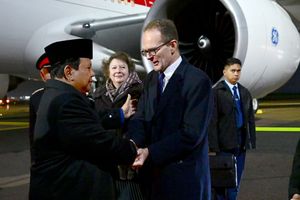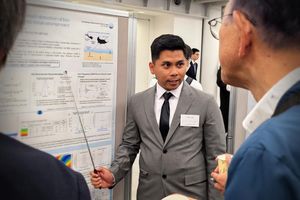Menyusuri Jepara Lewat Tiga Sajian Khas Daerah
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Ada hal menarik agar kita bisa kita dapat untuk mengenal sebuah kota atau daerah, yakni dimulai dari meja makan.
Cara terbaik menemukan kuliner khas suatu daerah sering kali bukan dengan mengandalkan mesin pencari, melainkan bertanya langsung kepada penduduk aslinya. Itulah yang saya lakukan ketika berkunjung ke Jepara.
Google memang menawarkan banyak referensi, tetapi rekomendasi seorang kawan terasa lebih personal dan adil. Mereka biasanya mempertimbangkan selera, kebiasaan, bahkan kondisi kita ketika memberi saran—sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh algoritma.
Semasa kuliah, saya memiliki seorang teman dekat yang berasal dari Jepara. Seiring waktu, komunikasi kami memang tak lagi seintens dulu.
Namun, sesampainya di Jepara, saya teringat untuk kembali menghubunginya. Momen seperti inilah yang sering kali menghidupkan kembali relasi lama—sekaligus membuka percakapan baru.
Meski kini tinggal di kota lain mengikuti suaminya, ia lahir dan besar di Jepara. Pengetahuannya tentang kuliner lokal tentu tidak diragukan. Beberapa nama makanan langsung ia sebutkan, dan saya pun tertarik untuk mencicipi sebagian di antaranya.
Horog-horog dan Jejak Sejarah di Piring Makan
Pecel bisa ditemukan hampir di semua daerah, tetapi pecel horog-horog hanya ada di Jepara. Kuliner inilah yang menjadi rekomendasi pertama: sarapan pecel horog-horog di pasar tradisional.
Dalam seporsi pecel ini, horog-horog berfungsi sebagai sumber karbohidrat, mirip dengan lontong atau gendar di daerah lain.
Karena posisinya sebagai pengganti nasi, horog-horog bisa dipadukan dengan berbagai lauk, mulai dari bakso, soto, gulai, hingga sate kikil. Untuk menemukannya, saya dan suami mengandalkan pencarian daring.
Kami datang dengan ekspektasi tertentu, meski sesampainya di sana harus mengakui sedikit kecewa. Warung yang kami datangi sangat sederhana dan kurang terawat.
Sebenarnya, kesederhanaan bukan masalah, namun ada batas-batas kenyamanan yang sulit diabaikan. Dalam hati, saya sempat menyesal tidak mengikuti saran teman untuk datang pagi hari di pasar, karena sore hari pilihannya memang lebih terbatas.
Meski begitu, tujuan utama tetap tercapai: mencicipi horog-horog.
Kami memesan satu porsi saja, sekadar mencoba. Tak lama kemudian, seporsi pecel dengan horog-horog terhidang. Warnanya putih cenderung pucat, dengan rasa yang sangat netral dan tekstur padat yang mudah pecah saat digigit.
Berbeda dari deskripsi kenyal yang saya baca, horog-horog yang saya cicipi terasa lebih kering. Entah karena kurang segar atau memang seperti itulah karakternya.
Namun, justru di situlah letak keunikan makanan ini. Horog-horog memang penganan sederhana dan merakyat—dan kesederhanaan itu tak lepas dari sejarahnya.
Konon, pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Jepara diwajibkan menyerahkan hasil panen padi kepada tentara Jepang.
Nasi pun menjadi makanan yang hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Dalam kondisi sulit itulah, masyarakat memanfaatkan tepung aren sebagai bahan pangan pengganti nasi.
Dari proses pembuatannya yang menghasilkan bunyi “horog-horog”, lahirlah nama makanan ini.
Kawan saya menyarankan agar pecel horog-horog disantap bersama sate cecek atau kikil. Sayangnya, lauk tersebut tidak tersedia di warung yang kami datangi. Meski hambar, rasa horog-horog ternyata mudah menyatu dengan bumbu pecel.
Bagi saya, rasanya masih bisa diterima, meski belum sepenuhnya akrab. Pada akhirnya, seporsi itu lebih banyak dihabiskan oleh suami.
Gudeg dan Lontong Opor di Warung Legendaris
Kuliner berikutnya membawa kami ke sebuah warung makan rumahan yang cukup dikenal oleh warga lokal: Warung Nasi Gudeg dan Lontong Opor Ibu Hj. Suyek. Lokasinya tidak berada di jalan utama, melainkan di teras rumah penduduk.
Sekilas tampak sederhana, tetapi deretan panci dan baskom besar berisi lauk pauk menjadi penanda bahwa tempat ini memiliki banyak pelanggan. Kami memesan seporsi gudeg lauk telur dan lontong opor ayam.
Saat itu gudeg nangka sedang kosong, sehingga seporsi gudeg saya berisi nasi, tahu, krecek, sayur cabai hijau, dan ayam kuah. Sementara lontong opor berisi lontong, tahu, kacang panjang, telur, dan ayam.
Berbeda dari gudeg Yogyakarta yang identik dengan rasa manis, sajian di sini cenderung gurih. Santan terasa dominan, dengan kuah yang kental dan kaya rasa. Bagi lidah saya, kehadiran sayur cabai justru menyempurnakan keseluruhan cita rasa.
Tak lama berselang, warung mulai dipenuhi pembeli. Mayoritas memilih dibungkus untuk sarapan. Penjual dan pembeli sama-sama berpacu dengan waktu, karena warung ini biasanya tutup sekitar pukul 10 pagi.
Ritme seperti ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun, menandakan usaha tersebut telah melewati tiga generasi. Bertahan selama itu tentu bukan perkara mudah. Jika rasanya biasa saja, tentu sulit menjaga pelanggan lintas generasi.
Menariknya, alih-alih membuka cabang atau memperbesar usaha, mereka memilih tetap berjualan dengan cara lama—sederhana, apa adanya, dan konsisten.
Menghangatkan Tubuh dengan Adon-adon Coro
Jika kawasan Joglosemar dikenal dengan wedang ronde, Jepara memiliki minuman khas bernama adon-adon coro. Keduanya sama-sama berbahan rempah dan berfungsi menghangatkan tubuh.
Minuman ini kini mulai sulit ditemukan. Karena itu, ketika saya menjumpai gerobak adon-adon coro di Jalan Ki Mangunsarkoro, tepatnya di depan Baznas Jepara, rasanya seperti menemukan harta karun kecil.
Harga seporsinya sangat terjangkau, hanya sekitar Rp7.000, dengan porsi setara satu mangkuk wedang ronde. Meski murah, minuman ini memiliki nilai sejarah. Pada masa kolonial, adon-adon coro konon hanya dikonsumsi kalangan bangsawan dan menjadi minuman favorit R.A. Kartini.
Secara tampilan, kuahnya berwarna kecokelatan dan agak keruh. Isinya terdiri dari jahe, gula merah, santan, rempah-rempah, serta potongan kelapa kecil.
Satu tegukan langsung menghadirkan rasa hangat di tenggorokan. Manisnya pas, aroma jahe terasa lembut, dan gurih santan semakin kuat saat potongan kelapa tergigit. Setelah satu mangkuk habis, tubuh dan perut terasa lebih hangat sangat cocok dinikmati di musim hujan, yang belakangan memang sering menyapa Jepara.
Menyusuri Kota Lewat Rasanya
Meski belum mencicipi seluruh kuliner khas Jepara, saya bersyukur bisa mengenal tiga di antaranya. Tidak hanya soal rasa dan kenyang, pengalaman ini menyadarkan bahwa kondisi alam dan perjalanan sejarah turut membentuk identitas kuliner suatu daerah.
Dari horog-horog yang lahir dari keterbatasan, gudeg rumahan yang bertahan lintas generasi, hingga adon-adon coro yang sarat nilai sejarah, Jepara menyimpan cerita yang bisa dinikmati perlahan lewat rasa.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mencicipi 3 Kuliner Khas Kota Ukir"
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarangVideo Pilihan Video Lainnya >