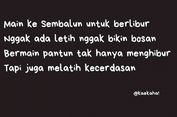Kekerasan di Sekolah: Imbas Fatherless dan Maskulinitas Toksik?
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Kekerasan dalam Dunia Pendidikan, Maskulinitas Toksik dan Fenomena "Negeri Tanpa Ayah""
Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan kabar kekerasan yang berujung pada meninggalnya santri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur. Santri berinisial AM tersebut diduga meninggal dunia akibat dianiaya oleh seniornya.
Sang ibu yang diberitahu bahwa AM meninggal akibat kelelahan setelah berkemah merasa curiga kalau ada yang ditutup-tutupi dari kematian anaknya.
Hal itu lantaran kain kafan sang anak yang sampai harus diganti karena ada darah merembes pada kain kafannya.
Kasus kekerasan merupakan salah satu aib dan dosa yang mencemari iklim akademis dunia pendidikan kita.
Alih-alih menjadi tempat untuk mendidik dan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak, sebuah institusi pendidikan terlihat seolah tak lebih dari sarang penjahat.
Bukan hanya di sekolah asrama, sekolah non-asrama pun tidak luput dari adanya kasus kekerasan. Mulai dari perundungan, tawuran antar pelajar, hingga pelecehan seksual.
Bicara tentang kekerasan dalam dunia pendidikan biasanya kita akan mengaitkan dengan sistem atau aturan yang berlaku.
Padahal kita bisa menilik jauh lebih dalam lagi soal maskulinitas toksik yang entah sadar atau tidak telah ditanamkan sejak usia dini serta ketidakterlibatan ayah dalam hal pengasuhan anak.
Bagaimana relasi antara ketiganya?
Mengenal Maskulinitas Toksik
Sebelum membahas keterkaitan aturan sekolah, maskulinitas toksik, dan ketidakterlibatan ayah, mari kita pahami dulu apa itu maskulinitas toksik.
Maskulinitas toksik adalah istilah yang merujuk pada dampak negatif dari sikap berpegang teguh pada karakteristik maskulin, ditambah dengan penekanan pada kejantanan yang didefinisikan sebagai kekerasan, seks, status, dominasi, ketangguhan dan agresi.
Pada dasarnya, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai sifat-sifat maskulin dan feminin dalam dirinya.
Sifat-sifat feminin antara lain meliputi sifat lemah lembut, penyayang, penyabar, empatik dan sebagainya. Sementara yang termasuk sifat-sifat maskulin antara lain kuat, tegas, berani, rasional, berjiwa pemimpin dan sebagainya. Kedua karakteristik ini sama baiknya.
Namun, ketika laki-laki selalu dituntut untuk menunjukkan maskulinitas demi menghindari stigma "laki-laki lemah" atau perempuan yang selalu dituntut untuk menunjukkan feminitas agar tidak dicap sebagai "perempuan kebablasan dan tak tahu adat", di sinilah maskulinitas dan feminitas berubah menjadi toksik.
Pernah dengar orangtua mengatakan anak laki-lakinya "cengeng" karena si anak menangis?
Mungkin orangtua tersebut bermaksud baik ingin mendidik anak laki-lakinya untuk menjadi anak yang kuat, percaya diri dan berani.
Namun, kadang mereka lupa kalau laki-laki juga manusia yang memiliki perasaan sehingga wajar apabila dia menangis karena sedih, terharu, kesakitan, atau merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja.
Alih-alih menanyakan penyebab anak menangis atau mengajarkannya cara mengekspresikan emosi negatif dengan sehat, seringnya orangtua tidak memvalidasi perasaan anak mereka.
Dalam pola asuh yang mengajarkan maskulinitas toksik, laki-laki ditabukan untuk menangis dan berkeluh kesah karena itu adalah tanda kelemahan.
Mereka hanya boleh mengekspresikan kekuatan, keberanian, ketangguhan, wibawa, kekuasaan, dan amarah.
Karena tidak pernah dilatih untuk mengekspresikan emosi negatif secara sehat, ketika laki-laki merasa malu, tersinggung, atau terluka solusi yang ditempuh adalah dengan kekerasan.
Cemburu karena istri/pacar tampak akrab dengan laki-laki lain, istri/pacarnya dipukuli. Tim sepak bola yang dijagokan kalah, baku hantam dengan pendukung tim lawan. Ditagih utang tetangga, bukannya dibayar malah tetangganya dilempar parang.
Laki-laki pengidap maskulinitas toksik memang lebih suka menyelesaikan masalah pakai otot (baca: menormalisasi kekerasan) daripada pakai otak.
Jangankan bisa berdiskusi secara elegan, intelek, dan beradab, kalau yang mereka utamakan hanyalah ego dan emosi.
Maskulinitas toksik juga cenderung mewajarkan perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh laki-laki bahkan menganggapnya keren.
Misalnya, merisak orang lain yang secara fisik lemah dan berbeda atau yang secara status sosial dan ekonomi lebih rendah, menganggap cupu sesama murid laki-laki yang tidak mau ikut tawuran dengan anak SMA lain, dan sebagainya.
Negeri Tanpa Ayah (Fatherless Country)
Ketidakterlibatan ayah dalam hal pengasuhan anak dikenal sebagai fenomena negeri tanpa ayah atau fatherless country phenomenon.
Apa pula itu fenomena "negeri tanpa ayah"?
Sebagaimana dikutip dari Kompas, Indonesia menempati urutan ke-3 dunia sebagai negara dengan anak-anak tanpa ayah (fatherless country) terbanyak.
Menurut psikolog Amerika, Edward Elmer Smith, yang dimaksud dengan fatherless adalah hilangnya peran ayah di rumah, baik secara fisik maupun psikologis. Sementara fatherless country adalah negara dengan peran ayah yang minim.
Menurut catatan Kementerian Sosial tahun 2021, jumlah anak yatim piatu di Indonesia sekitar 4.043.622 anak.
Jumlah ini mengalami peningkatan hingga mencapai 32.216 anak pada tahun 2022 akibat kematian orangtua karena Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam.
Itu baru contoh fatherless secara fisik. Bagaimana dengan jumlah anak yang mengalami fatherless secara psikologis?
Sayangnya, data dan penelitian yang berkaitan dengan fenomena fatherless di Indonesia masih sangat jarang dan terbatas.
Faktor Penyebab Fenomena Fatherless
Isu fatherless country merupakan masalah global yang terjadi di mana-mana.
Di negara Barat, sebab utama fenomena fatherless adalah ayah dan ibu yang tidak menikah, yang akibatnya kebanyakan anak hanya hidup dengan ibunya.
Sementara di Indonesia, kebanyakan terjadi pada orangtua yang masih terikat pernikahan tapi tugas pengasuhan anak tidak dipenuhi oleh ayah.
Contohnya, ayah terlalu sibuk bekerja dan sering bepergian ke luar kota serta tidak menjadikan keluarga sebagai prioritas sehingga anak kurang dekat atau tidak mendapat kasih sayang serta didikan yang cukup dari ayahnya.
Fenomena fatherless country di banyak negara erat kaitannya dengan peran gender tradisional yang hanya menimpakan tanggung jawab pengasuhan anak di tangan ibu, sedangkan tanggung jawab ayah hanya sebagai pencari nafkah.
Padahal sosok dan peran ayah dalam pengasuhan anak sangat penting dan bermanfaat dalam beberapa aspek khusus.
Misalnya, karakteristik ayah yang cenderung less protective dibandingkan ibu akan membuat anak untuk lebih berani bereksplorasi dan mengambil risiko.
Sebagai laki-laki yang cenderung lebih mengedepankan rasionalitas, ayah juga dapat melatih anaknya untuk menggunakan pendekatan rasional dalam menyelesaikan suatu masalah.
Dengan demikian, ketika dihadapkan pada suatu konflik, anak akan terlatih untuk tidak sedikit-sedikit pakai kekerasan apalagi main keroyokan.
Jika dalam proses pengasuhan ibu mengajarkan tentang kelembutan, ayah mengajarkan tentang ketegasan.
Ketegasan inilah yang akan melindungi anak sehingga ia tahu bagaimana membuat batasan diri, berkomunikasi asertif, dan membela diri atau orang lain ketika hak-haknya dilanggar.
Sementara itu, anak yang mengalami fatherless, rata-rata cenderung punya rasa percaya diri yang rendah, menarik diri dari kelompok sosial, rentan terlibat penyalahgunaan narkoba, rentan menjadi pelaku tindak kriminal atau kekerasan, dan sebagainya.
Aturan Sekolah, Maskulinitas Toksik, dan Fenomena Fatherless
Mungkin tulisan ini tampak seperti cocoklogi bagi Anda.
Namun, apa yang membentuk pribadi seorang anak hingga ia dewasa kelak, tentu tidak lepas dari peran pola asuh orangtua, bukan?
Anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah bukan melulu karena aturan sekolahnya yang kurang tegas atau guru-gurunya yang tidak bisa menangani anak nakal atau sistem pendidikan Tanah Air yang hanya mengedepankan pengajaran pada aspek kognitif tapi abai pada pendidikan moral dan spiritual.
Mari kita kembalikan dulu masalah kekerasan ini ke pendidikan di rumah.
Apakah sejak kecil anak sudah mendapat pelajaran tentang kekerasan? Misalnya, anak yang dituntut untuk harus selalu menunjukkan sisi maskulinitas (yang akhirnya jadi toksik), anak yang sering menerima atau melihat kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya.
Lalu, bagaimana dengan kehadiran ayah, baik secara fisik maupun psikologis dalam pengasuhan anak?
Apakah di sela kesibukan, ayah masih sempat bermain dan berbicara bersama anak atau malah urusan anak dari A sampai Z hanya dibebankan pada ibunya?
Video Pilihan Video Lainnya >