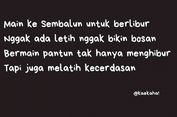Pameran Buku Indonesia: Riwayatmu Kini
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Apa Kabar Pameran Buku Indonesia?"
Sudah lama saya tidak berkunjung ke pameran buku, kecuali bazar buku seperti Big Bad Wolf.
Hal itu mungkin juga karena sudah mencapai titik jenuh. Sebab, sejak tahun 1998 bergiat di industri buku, saya tidak pernah absen menghadiri pameran buku di Jakarta, Bandung, dan terkadang Yogyakarta.
Kepentingannya bermacam-macam, mulai dari berjualan buku, mengamati tren, bersilaturahim dengan rekan-rekan pegiat buku, dan tentu saja berburu buku.
Suatu waktu hari Ahad, 13 Januari 2022 saya harus hadir di Indonesia International Book Fair (IIBF) yang digelar Ikapi, di Hall B, Jakarta Convention Center.
Di acara itu saya menjadi narasumber sebagai penulis buku Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman. Selain itu, acara ini juga menjadi awal dari pemecah kevakuman saya tampil di panggung pameran buku selama beberapa tahun.
Dari dalam diri ada kerinduan yang memantik untuk menikmati debur gagasan di lautan buku. Namun perlu diakui perbukuan Indonesia memang sedang banyak diempas ombak masalah,
Hal ini terlihat pada kongres asosiasi perbukuan sejagat (International Publisher Association, 10--12 November 2022) di IIBF karena Indonesia menjadi tuan rumah.
Di kongres tersebut, isu yang diangkat adalah soal hak cipta dan pembajakan buku yang terutama di Indonesia tidak pernah padam, bahkan malah makin menyala tanpa rasa.
Selain itu, perbukuan Indonesia juga tengah menghadapi disrupsi teknologi dan dipaksa beradaptasi dengan keadaan untuk melahirkan para pembaca buku generasi baru.
Akan tetapi, kerja-kerja kreatif penerbitan buku sejatinya tidak akan pernah padam karena buku telah menjadi kebutuhan primer untuk memenuhi dahaga pengetahun, informasi, dan hiburan.
Buku masih mempertahankan bentuknya yang tradisional dan juga mencoba bersolek dengan bentuknya yang digital.
Bicara mengenai pameran buku di Indonesia memang pernah ada masanya terlalu berlebihan, di mana hampir setiap bukan selalu ada pameran buku.
Hingga kemudian mencapai titik jenuh dan berimbas pada penjualan buku yang tak lagi dapat mengandalkan sebuah pameran.
Namun, di tengah masa-masa jenuh mengadakan pameran itu, para pelaku perbukuan justru dikejutkan dengan model bazar yang digelar oleh Big Bad Wolf.
Bazar buku internasional itu kemudian dibanjiri oleh pengunjung yang dianggap sudah jenuh dengan pameran buku ala Indonesia.
Sejarah Pameran Buku di Indonesia
Di Jakarta, IKAPI DKI masih bertahan dengan tradisi Islamic Book Fair sebagai pameran buku yang selalu disesaki pengunjung.
Di Yogyakarta muncul pameran buku Patjar Merah yang unik sehingga menyegarkan penyelenggaraan pameran buku selama ini.
Di Bandung, IKAPI Jabar yang menguasai tradisi pameran buku masih tidak mampu beranjak dari pola lama sehingga ketika Covid-19 melanda, praktis tak ada lagi pameran buku. IKAPI Pusat mempertahankan IIBF juga dengan tertatih karena sempat tak berkutik diempas badai Covid-19.
Dari sini timbul pertanyaan, apakah tradisi pameran buku di Indonesia masih akan menarik bagi para pengunjung terutama pengunjung milenial dan Gen Z?
 Pengunjung berburu buku di pameran buku BBW Jakarta 2020, Rabu (11/3/2020).
Pengunjung berburu buku di pameran buku BBW Jakarta 2020, Rabu (11/3/2020).Dalam sejarahnya di Nusantara, buku selalu menjadi magnet bagi banyak orang karena ada banyak "misteri" di balik kelahiran sebuah buku.
Oleh karenanya, pameran buku lah yang akan menjadi pintu untuk membuka misteri-misteri itu dan jendela untuk sekadar melongok kemeriahan gagasan yang dituliskan.
Sejarah pameran buku di Indonesia tercatat sudah berlangsung lama. Pada tahun 1953 tercatat pernah ada pameran buku akbar yang diprakarsai oleh Tjoe Wie Tay (Haji Masagung), pendiri Toko Buku dan Penerbit Gunung Agung.
Setahun setelahnya, tahun 1954 Tjoe Wie Tay kembali menggelar Pekan Buku Indonesia yang pada waktu itu dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta.
Dari itu, Tjoe Wie Tay diminta menggelar pameran buku di Medan tahun 1954 ketika berlangsung perhelatan Kongres Bahasa Indonesia.
Dari beberapa pameran yang diadakan tersebut, maka bisa dibilang bahwa Tjoe Wie Tay dan Gunung Agung merupakan perintis pameran buku Indonesia pertama setelah kemerdekaan.
Walaupun kini Toko Gunung Agung sudah rontok oleh zaman dan kita hanya bisa melihat tempat ia pertama kali didirikan, yaitu di Kwitang, Jakarta Pusat.
Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (2000, hlm. 186-216) mengisahkan kepada anaknya bahwa ia bertemu dengan ibunya pada saat Pekan Buku Indonesia 1954. Sang ibu, Maemunah Thamrin, menjadi salah seorang penjaga stan di pameran buku itu.
"Untuk pertama aku melihat ibumu dalam bulan Oktober atau Nopember 1954 di Pekan Buku, diselenggarakan oleh perusahaan buku Gunung Agung. Ibumu menjaga salah sebuah stand," begitu tulis Pram.
Perjumpaan jodoh itu disebut-sebut mengubah hidup Pram yang terpuruk. Ternyata pameran buku menyisipkan banyak kisah bagi para penulis, termasuk Pramoedya Ananta Toer.
Bagi saya pribadi, pameran buku juga banyak menyisipkan kisah di balik karier saya di dunia perbukuan.
Apa kabar pameran buku? Dikau selalu memantik rindu.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarangVideo Pilihan Video Lainnya >