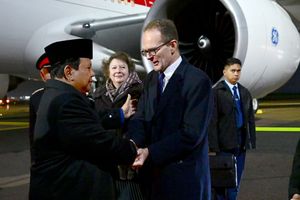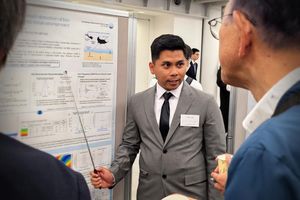Menyusuri Jepara Lewat Tiga Sajian Khas Daerah
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Namun, justru di situlah letak keunikan makanan ini. Horog-horog memang penganan sederhana dan merakyat—dan kesederhanaan itu tak lepas dari sejarahnya.
Konon, pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Jepara diwajibkan menyerahkan hasil panen padi kepada tentara Jepang.
Nasi pun menjadi makanan yang hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Dalam kondisi sulit itulah, masyarakat memanfaatkan tepung aren sebagai bahan pangan pengganti nasi.
Dari proses pembuatannya yang menghasilkan bunyi “horog-horog”, lahirlah nama makanan ini.
Kawan saya menyarankan agar pecel horog-horog disantap bersama sate cecek atau kikil. Sayangnya, lauk tersebut tidak tersedia di warung yang kami datangi. Meski hambar, rasa horog-horog ternyata mudah menyatu dengan bumbu pecel.
Bagi saya, rasanya masih bisa diterima, meski belum sepenuhnya akrab. Pada akhirnya, seporsi itu lebih banyak dihabiskan oleh suami.
Gudeg dan Lontong Opor di Warung Legendaris
Kuliner berikutnya membawa kami ke sebuah warung makan rumahan yang cukup dikenal oleh warga lokal: Warung Nasi Gudeg dan Lontong Opor Ibu Hj. Suyek. Lokasinya tidak berada di jalan utama, melainkan di teras rumah penduduk.
Sekilas tampak sederhana, tetapi deretan panci dan baskom besar berisi lauk pauk menjadi penanda bahwa tempat ini memiliki banyak pelanggan. Kami memesan seporsi gudeg lauk telur dan lontong opor ayam.
Saat itu gudeg nangka sedang kosong, sehingga seporsi gudeg saya berisi nasi, tahu, krecek, sayur cabai hijau, dan ayam kuah. Sementara lontong opor berisi lontong, tahu, kacang panjang, telur, dan ayam.
Berbeda dari gudeg Yogyakarta yang identik dengan rasa manis, sajian di sini cenderung gurih. Santan terasa dominan, dengan kuah yang kental dan kaya rasa. Bagi lidah saya, kehadiran sayur cabai justru menyempurnakan keseluruhan cita rasa.
Tak lama berselang, warung mulai dipenuhi pembeli. Mayoritas memilih dibungkus untuk sarapan. Penjual dan pembeli sama-sama berpacu dengan waktu, karena warung ini biasanya tutup sekitar pukul 10 pagi.
Ritme seperti ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun, menandakan usaha tersebut telah melewati tiga generasi. Bertahan selama itu tentu bukan perkara mudah. Jika rasanya biasa saja, tentu sulit menjaga pelanggan lintas generasi.
Menariknya, alih-alih membuka cabang atau memperbesar usaha, mereka memilih tetap berjualan dengan cara lama—sederhana, apa adanya, dan konsisten.
Menghangatkan Tubuh dengan Adon-adon Coro
Video Pilihan Video Lainnya >