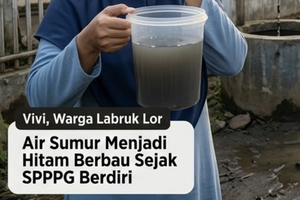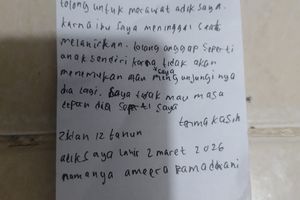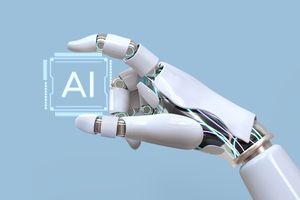Influencer Punya Rate Card, Dosen Juga Boleh Dong?
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Apakah wajar jika seorang influencer dibayar belasan juta rupiah untuk tampil di acara kampus, sementara seorang dosen berpendidikan S3 hanya menerima ratusan ribu?
Dan apakah profesi akademik memang selayaknya tidak memiliki “nilai” yang bisa dinegosiasikan, sebagaimana kreator digital punya rate card?
Pertanyaan ini kembali mencuat setelah sebuah unggahan di Threads menarik perhatian publik beberapa hari lalu.
Ketika Dosen Dibayar 300 Ribu, Influencer Belasan Juta
Cerita itu datang dari Junayd Floyd, seorang dosen dengan gelar S3 dari Monash University dan lebih dari 100 ribu pengikut di Instagram.
Ia menuturkan pengalamannya diundang ke sebuah acara kampus berbayar. Di panggung yang sama hadir pula beberapa influencer dengan bayaran belasan juta rupiah, lengkap dengan daftar kebutuhan atau rider mereka.
Sementara ia sendiri ditawari honor Rp300 ribu.
Dalam unggahannya, ia menulis sebuah kalimat yang membuat banyak orang berhenti sejenak:
“Ini bukan tentang duit 300 ribu yang mereka kasih untuk saya. Ini tentang menghargai waktu dan tenaga yang saya kasih untuk peserta.”
Dan kalimat penutupnya menjadi semacam wake-up call:
“It’s not the lack of money, it’s the lack of understanding of respect.”
Ungkapan tersebut bukan hanya curahan hati seorang dosen, tetapi cermin cara kita selama ini memandang profesi akademik dibandingkan profesi lain yang bergerak di dunia digital.
Mengapa Influencer Dibayar Lebih Tinggi?
Tanpa emosi, kita bisa memahami logikanya. Influencer dibayar berdasarkan data yang konkret: jangkauan audiens, tingkat interaksi, dan potensi exposure acara. Faktor-faktor itu memang punya nilai komersial yang jelas.
Sebaliknya, dosen—meski membawa ilmu, pengalaman, dan reputasi—sering kali tidak dinilai dari sisi tersebut. Pengetahuan dianggap sebagai “public good”, entitas yang seakan otomatis tersedia dan bisa dibagikan kapan saja.
Padahal, setiap sesi kuliah umum membutuhkan riset, persiapan materi, dan kompetensi akademik yang dibangun bertahun-tahun. Ketika usaha tersebut didevaluasi menjadi angka kecil, apalagi di acara berbayar, ketimpangannya terasa begitu terang.
Ini bukan soal nominal, tetapi soal proporsi dan etika menghargai profesi.
Dua Dunia, Dua Bahasa: Akademisi dan Industri Konten Kreatif
Video Pilihan Video Lainnya >